Selama perkembangannya, budidaya ikan di Indonesia, terutama ikan air tawar, sebagian besar masih mengandalkan metode konvensional yang banyak bergantung pada lahan yang luas dan sumber air alami seperti sungai, waduk, atau perairan umum lainnya. Namun, di tengah tantangan efisiensi dan isu lingkungan, muncul satu inovasi yang mulai menarik banyak perhatian, yakni teknologi bioflok.
Praktisi industri pakan ikan dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, Hartadi, dalam seminar yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Akuakultur (Himakua) IPB University beberapa waktu lalu, menjelaskan bahwa teknologi bioflok berpotensi besar dalam meningkatkan produktivitas budidaya ikan nila secara efisien dan berkelanjutan.
Efisiensi lahan dan air
Hartadi menjelaskan bahwa sudah banyak bukti keberhasilan penerapan teknologi bioflok, khususnya pada ikan nila dan udang vaname. Kelebihan utama sistem ini terletak pada efisiensi penggunaan lahan, air, dan pakan. Jika budidaya konvensional membutuhkan kolam besar atau area tambak luas, sistem bioflok justru bisa dijalankan di lahan terbatas, bahkan bisa di pekarangan rumah.
Menurutnya, dengan lahan 100 meter persegi saja, sistem bioflok sudah bisa menghasilkan produksi ikan setara dengan tambak konvensional seluas satu hektar. Dalam sistem ini, satu meter persegi kolam bisa menghasilkan 20–30 kilogram ikan. Perbandingannya jauh jika dibanding kolam atau tambak tradisional yang rata-rata hanya mampu menghasilkan 0,5–1 kilogram per meter persegi.
Selain itu, sumber air yang dibutuhkan pun tidak harus berasal dari sungai atau waduk besar. Air sumur pun cukup selama dikelola dengan baik. Dengan begitu, hal ini juga membuka peluang bagi masyarakat perkotaan yang memiliki lahan sempit namun ingin memiliki kegiatan budidaya ikan sendiri (urban farming).
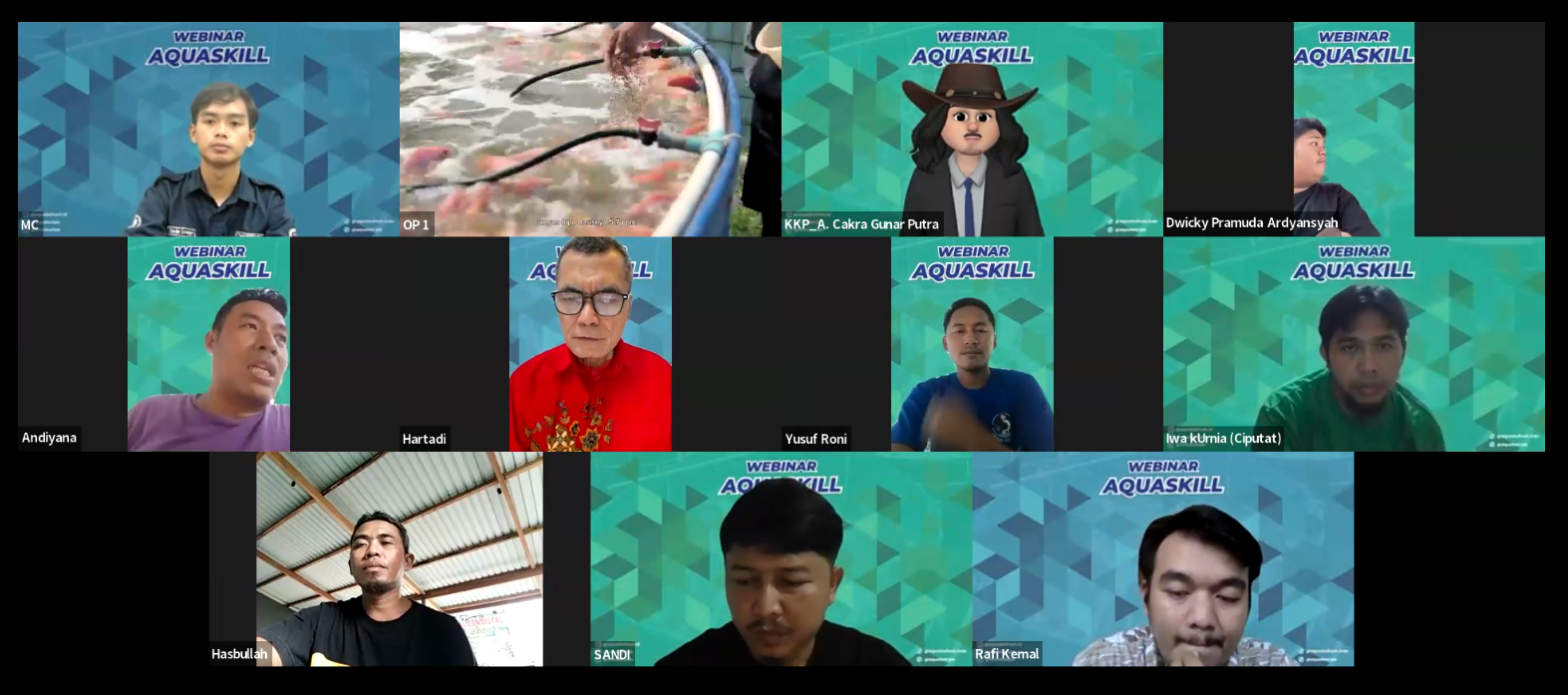
Ramah lingkungan dan produktivitas tinggi
Hartadi juga menambahkan bahwa keunggulan lain dari sistem bioflok adalah adalah sifatnya yang ramah lingkungan. Sistem ini tidak menghasilkan sisa bahan organik sebanyak metode konvensional. Dalam praktik lama, pakan yang tidak termakan dan feses ikan biasanya langsung terbuang ke perairan terbuka seperti waduk, danau, atau sungai, yang berpotensi membuat perairan mengalami eutrofikasi (terlalu subur) dan memunculkan gulma air.
“Kita tentunya ingin memaksimalkan keuntungan ekonomi yang stabil dan jangka panjang. Kemudian keberlanjutan secara lingkungan, bagaimana kita mampu untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan juga meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem,” ujarnya.
Selain ramah lingkungan, produktivitas sistem ini juga relatif tinggi. Hartadi mencatat, tingkat kelangsungan hidup (survival rate) ikan pada sistem bioflok bisa mencapai lebih dari 90%, jauh di atas budidaya konvensional yang menurut pengamatannya sering kali hanya 30–50%. Efisiensi pakan pun meningkat, dengan rasio konversi pakan (feed conversion ratio atau FCR) mencapai 1–1,1. Artinya, 1 kilogram pakan bisa menghasilkan hampir 1 kilogram daging ikan.
Baca juga:
1. Bioflok nila hemat, tanpa tambahan probiotik dan molase
2. Budidaya ikan di KJA: Mencari titik temu antara keuntungan dan kelestarian
3. Outlook Tilapia 2025: Memperkuat hulu-hilir dan keberlanjutan budidaya nila
Kualitas daging lebih disukai konsumen
Selain keunggulan pada aspek produksi dan lingkungan, ikan nila hasil budidaya bioflok juga punya keunggulan di hilir karena memiliki cita rasa yang lebih disukai konsumen. Hartadi mengatakan bahwa daging ikan nila bioflok dikenal lebih gurih dan tidak berbau lumpur seperti ikan yang dibudidayakan di tambak atau waduk.
“Kalau dijual ke restoran atau konsumen langsung, biasanya lebih mudah diterima. Mereka bisa membedakan rasa dan aroma daging ikan yang dihasilkan,” kata Hartadi.
Keunggulan ini membuat bioflok bukan hanya efisien secara teknis, tetapi juga punya potensi unggul secara komersial karena produknya memiliki nilai jual lebih tinggi.
Tantangan bioflok
Meski memiliki banyak kelebihan, Hartadi tidak memungkiri bahwa penerapan sistem bioflok juga punya tantangan tersendiri. Salah satu yang utama adalah ketergantungan pada listrik. Sistem bioflok membutuhkan aerasi secara terus-menerus untuk menjaga kadar oksigen terlarut dalam air tetap tinggi dan stabil. Gangguan listrik bisa berakibat fatal karena ikan akan kekurangan oksigen dan mati dalam waktu singkat.
“Kasus kematian ikan paling banyak disebabkan mati listrik atau blower rusak. Karena itu, wajib punya genset sebagai cadangan,” tegasnya.
Selain itu, sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor penentu keberhasilan. Operator kolam harus memahami cara mengatur aerasi, menjaga kualitas air, dan mengikuti prosedur operasional standar (SOP) secara disiplin. Kesalahan kecil dalam pengaturan sistem dapat berujung pada kegagalan panen.
“Teknologi ini tidak bisa dijalankan asal-asalan. Operator perlu pelatihan intensif agar paham cara mengelola sistemnya,” tambahnya.
Kualitas benih dan pakan menentukan hasil
Keberhasilan sistem bioflok juga sangat bergantung pada kualitas benih dan pakan. Benih yang digunakan sebaiknya berasal dari sumber terpercaya dan memiliki ukuran seragam, minimal 20 gram per ekor. Benih yang terlalu kecil atau tidak seragam bisa menimbulkan persaingan pakan yang tidak seimbang, sehingga menurunkan efisiensi FCR, dan memperbesar risiko kematian.
Selain itu, Hartadi menyarankan pembudidaya untuk menggunakan benih jantan unggul agar pertumbuhannya lebih optimal. Menurutnya, benih betina cenderung lebih cepat bertelur sehingga energi banyak terserap untuk reproduksi, bukan pertumbuhan.
Sementara itu, pakan harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem bioflok. Hartadi yang berpengalaman di industri pakan menjelaskan bahwa pakan untuk bioflok memiliki formula berbeda dengan pakan untuk budidaya konvensional. “Kalau kualitas pakannya tidak sesuai, bisa berdampak langsung pada pertumbuhan dan efisiensi budidaya,” ujarnya.
Rekomendasi teknis
Hartadi juga membagikan beberapa rekomendasi teknis agar sistem bioflok berjalan optimal. Beberapa parameter penting yang perlu dijaga antara lain:
- Daya dukung biomassa: 20–30 kilogram ikan per meter kubik air.
- Kadar flok (gumpalan mikroorganisme): 10–20 ml per liter air.
- pH air: 6,8–7,4.
- Suhu air: 27–30°C.
- Oksigen terlarut (DO): minimal 3 ppm, ideal 5 ppm.
Flok yang terlalu banyak akan membuat air keruh dan mengganggu sistem pernapasan ikan. Sebaliknya, jika terlalu sedikit, kinerja sistem bioflok tidak optimal karena mikroorganisme tidak cukup untuk membantu penguraian limbah organik.
Ia juga menyoroti beberapa masalah umum yang sering terjadi di lapangan, seperti outlet pembuangan air yang lepas, dinamo blower terbakar, hingga cuaca mendung berkepanjangan yang menurunkan suhu air. Semua faktor ini, katanya, bisa diantisipasi dengan perawatan rutin, sistem cadangan listrik, dan penggunaan tandon air.
Menuju budidaya yang modern dan berkelanjutan
Sebagai penutup, Hartadi menekankan bahwa teknologi bioflok adalah bagian dari proses modernisasi budidaya ikan di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa perubahan dari cara tradisional ke teknologi modern membutuhkan waktu dan adaptasi, seperti halnya transformasi dari pakan alami ke pakan industri pada era 1980-an.
Kini, saat permintaan ikan terus meningkat dan pasokan harus stabil, bioflok bisa menjadi salah solusi masa depan bagi pembudidaya. “Budidaya ikan sudah masuk ke arah industri. Pasar butuh kontinuitas dan kualitas. Bioflok memberi peluang untuk menjawab tantangan itu,” pungkasnya.







