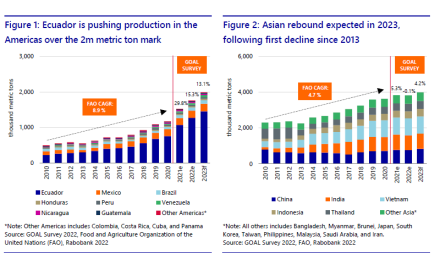Mikroplastik di laut, yang merupakan hasil dari pencemaran manusia, kini menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan. Partikel mikroplastik berukuran sekitar satu mikron—lebih besar dari ukuran virus—dapat menjadi perantara bagi virus untuk bereplikasi dan berkembang biak. Menurut para ahli, mikroplastik dan nanoplastik yang ada di laut dapat menyebabkan masalah kesehatan pada udang, karena partikel tersebut dapat menjadi media patogen untuk berkembang biak dan menyerang udang.
Kamaru Budianto, Marketing and Sales Director Yuki Water Treatment menuturkan hal tersebut saat menjadi salah satu pembicara dalam acara Rapat Kerja Nasional Shrimp Club Indonesia (SCI), di Lombok, beberapa waktu yang lalu. Menurut Kamaru, Indonesia termasuk dalam lima besar negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia.
Selain itu, tantangan perubahan iklim juga menjadi masalah serius karena telah menyebabkan peningkatan suhu air laut. Kondisi air laut yang hangat menjadi kondisi yang ideal bagi pertumbuhan patogen. Peningkatan suhu air laut juga mempengaruhi faktor lain seperti TDS, oksigen terlarut (dissolved oxygen/DO), pH, dan lain-lain.
Menurut Kamaru, tantangan-tantangan tersebut membuat budidaya udang semakin sulit dan berpotensi meningkatkan biaya untuk manajemen kualitas air, serta meningkatkan biaya produksi yang sudah tinggi.
Meninjau ulang efisiensi kaporit
Peningkatan potensi patogen di tambak udang, akibat perubahan iklim, membuat upaya manajemen air juga terus meningkat. Termasuk dalam penggunaan kaporit untuk disinfeksi. Menurut Kamaru, petambak di Indonesia umumnya menggunakan kaporit karena harga perkilogramnya yang relatif murah. Namun kata dia, penggunaan kaporit yang hanya sekali pakai, membuat petambak harus terus menerus menggunakannya. Sehingga jika diakumulasikan, biayanya menjadi sangat mahal.
“Ini adalah salah satu (perhitungan) yang dibuat oleh rekan kerja kami. Perhitungan satu kolam 2.000 meter persegi menggunakan 90 kg kaporit. Jadi jika ada 30 kolam, biayanya kurang lebih sekitar Rp100 juta,” ungkap Kamaru.
Biaya itu hanya untuk persiapan kolam di awal saja. Yang lebih mahal, kata Kamaru, justru pada penggunaan tambahan kaporit di sepanjang siklus. Biaya kaporit selama produksi berlangsung (untuk sekitar 30 kolam), bisa mencapai Rp1 miliar. Jika dalam satu tahun ada dua kali siklus saja, maka biaya untuk kaporit saja bisa mencapai Rp2 miliar. Menurutnya, biaya sebesar itu bisa diinvestasikan pada teknologi water treatment yang lain seperti UV-C (ultraviolet-C).
Baca juga: Jejak karbon akuakultur: Sumber-sumber penghasil emisi dalam budidaya
Selain karena biayanya yang tinggi, kaporit di kolam cenderung akan bereaksi dengan bahan organik yang ada di air dan membentuk hasil samping (disinfection by-products) yang berbahaya dan bahkan lebih beracun dibanding kaporit itu sendiri. Menurut Kamaru, hal itu terbukti bersifat karsinogenik dan bisa menyebabkan kanker.

Kamaru Budianto saat presentasi di acara Rakernas Shrimp Club Indonesia (SCI), di Lombok (29/11). ©SCI
“Jadi bisa dibayangkan demi membunuh patogen di air, kami menggunakan kaporit untuk meracuni udang juga. Selain itu kaporit berbahaya untuk pekerja dan orang-orang di sekitarnya karena airnya cukup keras. Tidak semua patogen bisa dikendalikan oleh kaporit, contohnya EHP, EMS, dan Vibrio. Menggunakan kaporit secara berlebihan menyebabkan patogen-patogen ini secara bertahap kebal dengan melakukan penyesuaian,” jelas Kamaru.
Berhati-hati memilih teknologi UV
Kamaru menuturkan bahwa banyak petambak sudah mulai menggunakan UV-C karena keunggulannya yang lebih efisien dan tidak butuh waktu tunggu, sehingga air yang telah melwati UV siap untuk digunakan. Teknologi ini juga menawarkan penghematan biaya produksi karena umur teknisnya yang bisa mencapai 10 tahun.
“Jadi waktu saya survei satu pabrik yang sedang memasang teknologi UV, pas kami berkunjung ke lokasi, mereknya sudah tidak ada saking lamanya karena dipakai selama 20 tahun tidak bocor-bocor,” kata Kamaru.
Meski demikian, sebagian petambak mengatakan jika hasil panen mereka lebih buruk atau sama saja dengan atau tanpa UV-C. Hal itu bisa terjadi lantaran dosis dan spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh setiap produsen/supplier berbeda-beda.
Menurut Kamaru, setiap jenis patogen membutuhkan dosis UV yang berbeda-beda. Tidak ada dosis tunggal yang berlaku untuk semua jenis patogen. Sebagai contoh, Vibrio salmonicida membutuhkan dosis 1,5 mJ, Bacterial Kidney Disease (BKD) membutuhkan 60 mJ, sementara EHP—penyakit udang yang semakin sering ditemukan di Indonesia—memerlukan dosis lebih tinggi, yakni 300-400 mJ.
Selain masalah dosis, efektivitas UV di tambak juga ditentukan oleh spesifikasi teknis UV-nya itu sendiri. Menurut Kamaru, tidak sedikit UV yang digunakan petambak sebetulnya tidak diperuntukkan untuk air laut, melainkan untuk air tawar, sehingga UV mudah korosi, berkarat, hingga bocor. Selain itu, air laut juga cenderung memiliki kapur yang tinggi. yang dapat menyebabkan pengerakan pada alat UV.
“Selisih (kapur air laut dan tawar) bedanya adalah 350 kali, jauh sekali. Ini salah satu contoh pembentukan kerak pada permukaan selongsong jika kami menggunakan sistem UV yang tidak cocok untuk air laut atau tidak didukung dengan teknologi sistem air laut. Apabila selongsong ini sudah tertutup dengan kapur, ada dan tidak ada UV sama saja karena cahaya UV tidak bisa keluar untuk melakukan proses desinfeksi,” ungkap Kamaru.
Baca juga: Cara hemat listrik di tambak intensif
Potensi injektor venturi untuk tingkatkan DO
Selain membahas efisiensi biaya manajemen kualitas air melalui penggunaan UV-C, Kamaru juga membahas potensi penghematan biaya penggunaan kincir, yang banyak mengonsumsi energi listrik di tambak. Menurutnya, untuk satu tambak berukuran 3.000 ribu meter persegi, petambak memerlukan sekitar dua puluh lebih kincir air. Biaya listriknya dalam setahun bisa mencapai Rp100 juta. Jika ada 30-an kolam, maka biayanya bisa mencapai Rp3 miliar.
“Itu bukan uang yang sedikit! Dalam sepuluh tahun itu menjadi Rp30 miliar. Dan uang itu bisa digunakan untuk memperbaiki teknologi water treatment, sehingga tambak Anda lebih produktif dari segi panen,” tutur Kamaru.
Meski kincir sangat populer dan banyak digunakan para petambak, tapi ia menilai alat tersebut kurang efektif dalam meningkatkan DO. Sebabnya, pergerakan air dan peningkatan oksigen lebih banyak terjadi di permukaan, tidak merata hingga ke bagian dasar kolam.
Di sisi lain, blower cukup efektif dalam meningkatkan DO secara merata di seluruh badan air. Tetapi energi yang digunakan terlalu besar dan tidak efisien untuk kedalaman tambak yang hanya sekitar 1,5 meter saja. Menurut Kamaru, blower akan jauh lebih efisien jika digunakan pada kedalaman 5-6 meter.
Ia kemudian mempromosikan penggunaan teknologi injektor venturi untuk mengatasi permasalahan DO dan biaya energinya yang besar. Injektor venturi memungkinkan untuk menghasilkan gelembung-gelumbung berukuran mikro (microbubble), yang dapat ditembakkan ke dasar kolam dan menjaga kelarutan oksigen dalam air tetap tinggi dalam waktu cukup lama.
”Ini perbandingan microbubble lebih efektif karena ke atasnya lebih pelan, dan dia pecahnya bukan di atas permukaan kolam, tetapi di dalam. Ini mengapa mereka bisa meningkatkan DO,” kata Kamaru.
Ia menambahkan bahwa teknologi ini sudah digunakan di industri pengolahan air limbah karena selain efektif, juga efisien dari aspek biaya karena tidak membutuhkan energi listrik dan perawatan khusus.
***
Penulis: Rosita
Editor: Asep Bulkini